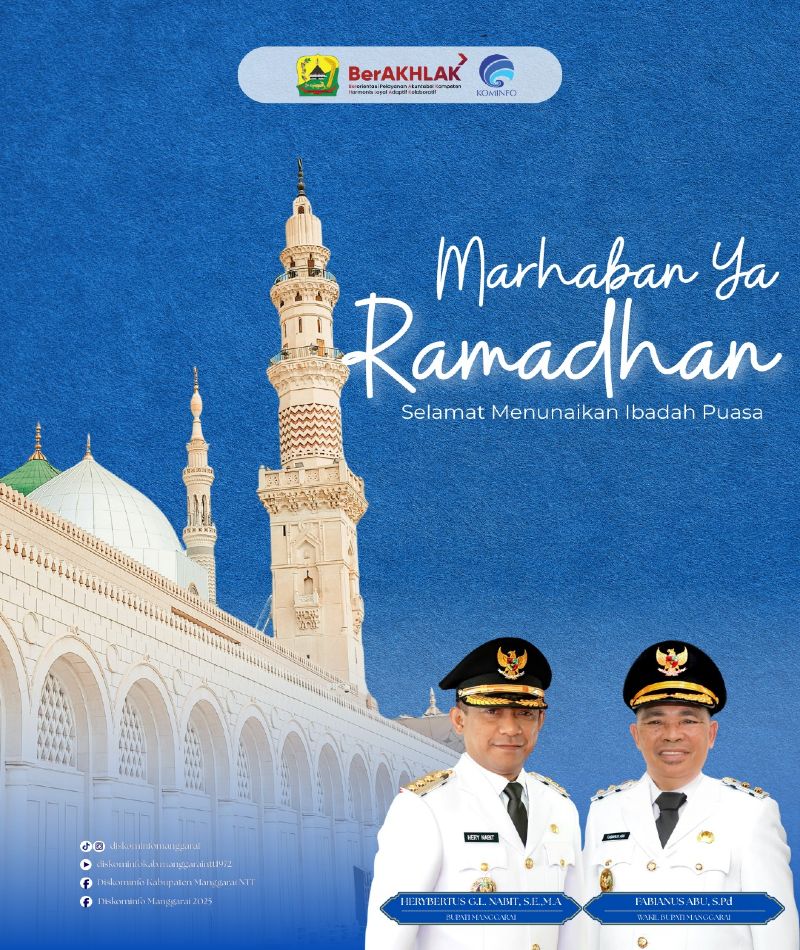Selain itu, efektivitas dari reformasi sistem PPN juga berimplikasi pada pemeriksaan pajak. Seperti diketahui, PKP berhak mengajukan restitusi PPN apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Dalam prosesnya, DJP akan melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap pengajuan restitusi tersebut.
“Kalau misalkan itu sudah terjadi (faktur pajak sebagai bukti pembayaran), maka tidak ada pemeriksaan. Terlebih semua data transaksi ekonomi sudah terkoneksi nantinya oleh sistem DJP, melalui core tax (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan/PSIAP),” kata Prof ESI.
Ia optimistis reformasi sistem PPN akan mengoptimalkan rasio perpajakan hingga titik ideal negara berkembang, yakni berkisar 15 persen terhadap PDB. Seperti diketahui, rasio pajak Indonesia saat ini masa bertengger di level 10,41 persen terhadap PDB atau paling rendah dibandingkan negara ASEAN dan G20.
Di ASEAN, rasio pajak tertinggi dicapai Vietnam sebesar 22,7 persen terhadap PDB, lalu disusul Kamboja 20,2 persen terhadap PDB, Thailand 16,5 persen terhadap PDB, Singapura 12,8 persen terhadap PDB, Malaysia 11,4 persen terhadap PDB.
Sementara di negara G20, seperti Amerika Serikat mencatatkan rasio pajak pada level 26,58 persen terhadap PDB; Denmark, Prancis, dan Finlandia mencapai di kisaran 40 persen hingga 47 persen terhadap PDB.
“Harus jujur diakui, bahwa reformasi perpajakan yang telah berlangsung 40 tahun dan di setiap periode kepemimpanan dilakukan reformasi dengan anggaran yang tidak sedikit, belum mampu mempersembahkan tax ratio yang lebih baik. Bahkan dalam tujuh tahun terakhir, ada kecenderungan menurun dan dalam dua tahun terakhir pada posisi stagnan.”
Padahal, dari perspektif pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari 5 persen. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok, di antara negara G20.
“Selain itu, kita sudah menjalankan tax amnesty (2016-2017), sekarang sudah 6 tahun, janji tax ratio akan meningkat, kenyataannya janji sulit dipenuhi,” ungkap Prof ESI.
Hati-Hati menaikkan PPN jadi 12 persen
Selain reformasi sistem PPN, Prof ESI juga mengingatkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhati-hati dalam menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Meskipun UU HPP telah mengamanatkan tarif PPN 12 persen sebelum 1 Januari 2025, ia meyakini bahwa kenaikan tarif bukan jalan terbaik untuk mencapai target penerimaan dan rasio perpajakan.
Menurutnya, menaikkan tarif PPN berpotensi mendistorsi daya beli masyarakat yang bermuara pada lesunya pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan negara. Terlebih berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terjadi penurunan tren Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang disebabkan juga oleh perlambatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI).
Pertumbuhan ekonomi nasional hingga Oktober 2023 pun tercatat di bawah 5 persen. Di samping itu, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berkisar 6,4 persen—angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penerimaan pada periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar 58,1 persen.
“Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen justru kontraproduktif dengan penerimaan pajak. Kenaikan tarif bukan jalan menaikkan penerimaan. Kenaikan tarif PPN sebagai pajak langsung menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang dan pertumbuhan ekonomi nasional akan menurun. Apalagi saat ini posisi Indonesia pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bagus, yakni berkisar 5 persen. Di sisi lain, dunia masih diselimuti ancaman ketidakpastian perekonomian global dan kenaikan suku bunga,” tandasnya.
Menurut Prof ESI, pemerintah justru perlu mengevaluasi kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen yang dimulai sejak 1 April 2022 lalu. Pemerintah harus mengkaji bagaimana dampak kenaikan tersebut terhadap rasio dan pertumbuhan penerimaan dari PPN.
“Kalau tarif PPN sudah naik dari 10 persen ke 11 persen, harusnya pertumbuhan PPN tumbuh 1 persen. Kemudian, tadinya rasio PPN 3 persen, lalu sekarang masih sama, maka perlu dievaluasi. Setidaknya rasio pajak naik menjadi 4 persen dan seterusnya. Kalau tidak berubah mungkin saja pemerintah menurun tarif PPN-nya lagi menjadi 10 persen. Jadi, menurut saya sangat mungkin kita ingin memperluas basis pemajakan sekaligus menurunkan tarif PPN sekaligus memperbaiki sistem PPN. Jangan hanya memperluas basis pajak dan menaikan tarif pajak, terus kita yakin penerimaan akan lebih bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan dan rasio perpajakan dapat diwujudkan dengan harmonisasi reformasi tax policy dan tax administration. Diperlukan adanya satu paket kebijakan komplet yang memayungi keduanya. Kebijakan perpajakan berkeadilan akan menciptakan kepastian hukum yang bermuara pada meningkatnya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Maka, sekarang yang harus dibenahi UU perpajakan, yang mana di dalamnya merombak sistem-sistem yang perlu diperbaiki. UU perpajakan harus secara tegas mengatur mana yang merupakan objek pajak dan bukan. Jangan sampai masyarakat masih bingung, hal ini menandakan UU perpajakan itu tidak familier dengan masyarakat. UU perpajakan harus sejelas-jelasnya,” pungkas Prof ESI yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Wadokai Karate-Do Indonesia.
Pembentukan badan otoritas penerimaan negara
Secara parsial, Prof ESI juga berpandangan bahwa diperlukan transformasi kelembagaan perpajakan untuk memenuhi kebutuhan negara maupun rakyat melalui penataan dan fungsi institusi.
Doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyebutkan, ada tiga model kelembagaan perpajakan yang dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Pertama, model pengelolaan pajak oleh satu direktorat jenderal yang melekat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua, model pengelolaan pajak oleh lembaga otoritas semi independen. Ketiga, model pengelolaan pajak oleh otoritas pajak independen atau lepas dari Kemenkeu. Prof ESI menyimpulkan, model tersebut sebagai badan otoritas penerimaan negara.
“Dalam Pasal 23A UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 mengenai pemungutan pajak, yang kita tahu kontribusinya 70-80 persen terhadap penerimaan negara, namun hanya dikelola oleh pejabat setingkat eselon I, DJP di bawah Kemenkeu. Akibatnya DJP tidak akan bisa merespons tuntutan lingkungan, masyarakat, dan negara di waktu yang sama. Pengelolaan yang bersifat mandiri dan independen, lebih tepat untuk Indonesia. Hal ini demi memenuhi kebutuhan pengelolaan pajak yang selama ini belum berhasil menjadikan APBN mandiri, sehingga nantinya utang tidak semakin banyak. Kebutuhan kesejahteraan rakyat harus terpenuhi oleh negara,” ujar salah satu pendiri klaster riset politic of taxation, welfare and national resilience (PolTax) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.
Di sisi lain, Prof ESI menganalisis, terjadi anomali pada struktur kelembagaan di tubuh DJP—tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 7 Tahun 2015 ditegaskan bahwa direktorat jenderal terdiri atas sekretariat direktorat jenderal dan paling banyak lima direktorat.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel