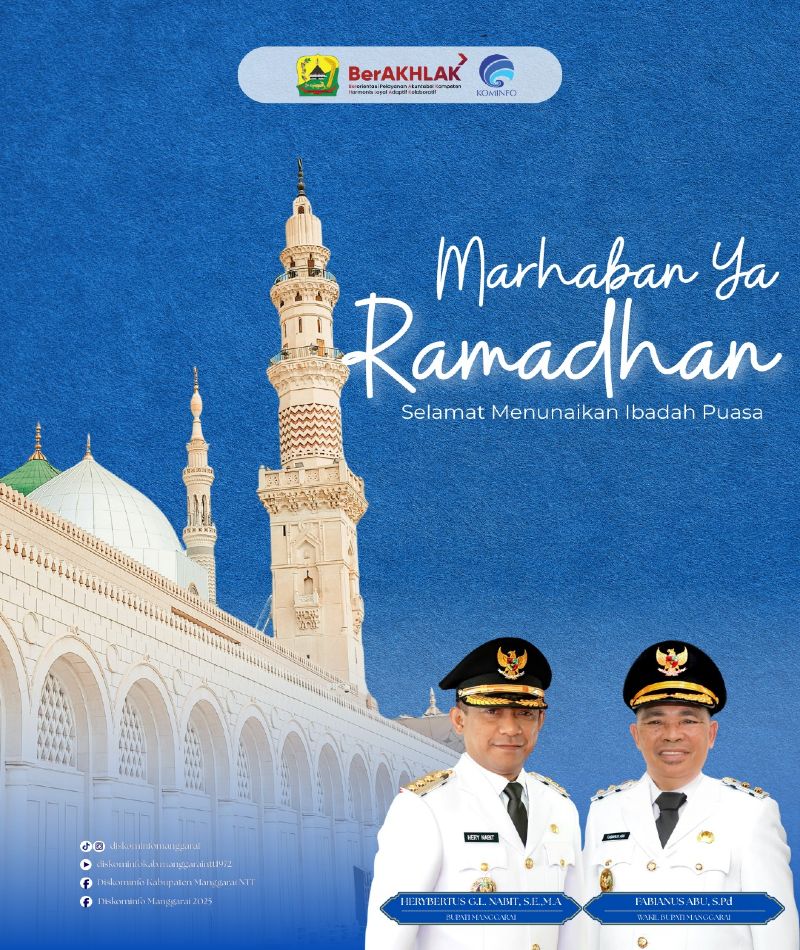Dan menjadi repotnya lagi, jika sekiranya fantasi dan pengandaian itu miliki kiblati ke isi dan lintasan negatif. Teori konspirasi dalam psikologi sosial isyaratkan bahwa “bias negavitas mengacu pada fakta bahwa kita menunjukkan sensivitas yang lebih besar pada informasi negatif daripada informasi positif” (Komaruddin Hidayat & Khoiruddin Bashori, 2016).
Lebih tertarik pada ‘titik-titik hitam’
Bahkan dikatakan, “Manakala peristiwa baik dan peristiwa buruk terjadi pada diri kita pada hari sama, kita cenderung akan bereaksi lebih kuat terhadap peristiwa buruk dari pada peristiwa baik, bahkan jika kedua peristiwa itu memiliki nilai yang sebanding.” Dan memang seperti itulah yang nyata di keseharian. Ingatan kita lebih terpikat pada hal-hal suram ketimbang hal-hal yang membesarkan hati dan memberi harapan.
Itulah sebabnya dapat dimengerti bahwa kelompok-kelompok khusus, apalagi bila dibalut ketat oleh lingkaran dan tautan etnosentrisme atau kepentingan sepihak, akan berlama-lama gunakan waktu dan kesempatan untuk memanfaatkan sebaik mungkin apa yang dianggapnya ‘kurang, lemah, bejatnya’ dari group lawan atau kelompok tandingan. Tentu demi proganda dan kampanye publik degradatif yang menggelikan dan bahkan menjijikan untuk memberangus yang dianggap lawan.
Masih dari telaah Komaruddin dan Khoiruddin, “Sekitar 80% perbincangan di dunia kerja lebih banyak berisi komentar kritis, sebab sebagian besar orang lebih memperhatikan hal yang belum berjalan dengan baik daripada hal yang sudah berjalan dengan baik.”
Tak usahlah bercitra di atas kekelaman lama
Banyak ‘(calon) pemimpin penerus’ atau ‘pengganti’ sepertinya kelewat sensitif, walau terkadang dipaksa, untuk membelalak pada ‘apa-apa’ yang dirasa belum, apalagi dianggap gagal dari pendahulunya. Rasanya terlalu sulit untuk melihat atau menyadari bahwa ada pula hal-hal baik yang mesti dilanjutkan. Itulah yang dalam psikologi sosial diyakini bahwa orang lebih sentimental oleh isu-isu atau stimulus beraroma negatif.
Kita kehilangan dan ketiadaan momentum teduh dan hening untuk ‘mengamati, menimbang, dan lalu mesti memutuskan secara bijak dalam titik-titik pandangan yang lebih luas dan menyeluruh. Ini berdampak dalam memandang sesuatu dalam ‘kebenaran.’ Mari kita melebar pada sepotong kebenaran.
Claiming kebenaran nan rapuh
Yang disebut kebenaran disinyalir telah ditumbangkan dari takhtanya. Sebab soal ‘kebenaran’ adalah soal arus deras claiming. Bukan pada fakta. Yang diklaiming oleh yang mayoritas, yang lebih heboh dan beringas dalam aksi dan gertaknya, itulah ‘yang benar’ dan ‘wajib benar dan harus diakui kebenarannya.’ Apalagi jika semuanya digaransi oleh instrumen kekerasan sebagai hukuman atau bahkan atas nama Yang Maha Kuasa. Dan ada hal lain lagi….
Betapa kita terlampau didera kejaran waktu yang sungguh menyibukkan. Kita terjebak dalam ‘ketergesaan’ sehingga “kita tidak punya waktu untuk melihat satu sama lain atau sesuatu dengan tepat.” Dan itu pun yang terjadi pada telinga yang sungguh kebisingan. Yang kehilangan keteduhan untuk menangkap dan menyimak kata-kata yang disuarakan.
Telinga yang telah terbeli?
Sebab itulah, sering terjadi bahwa dalam apa yang disebut ‘dialog’ atau diskusi demi kumpas tuntas gagasan tidak berujung pada kedaulatan ratio untuk sungguh memahami. Kampanye, propaganda, suara-suara keras dari panggung atau mimbar hanyalah upaya demi penaklukan telinga. Kuping yang mesti dijauhkan dari segala alam keteduhannya.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel