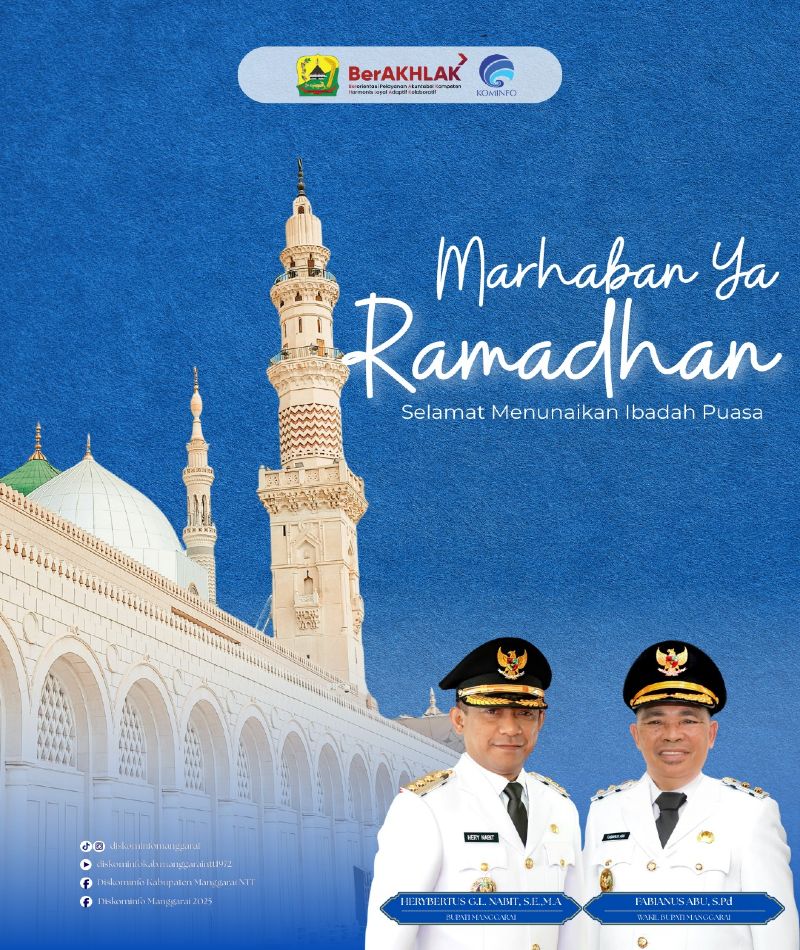sebatas satu perenungan
“Di suatu tempat, kita tahu bahwa tanpa keheningan, kata-kata kehilangan maknanya, bahwa tanpa mendengarkan, berbicara tidak lagi menyembuhkan, bahwa tanpa jarak, kedekatan tidak dapat menyembuhkan”
(Henri Nouwen, 1932 – 1996)
P. Kons Beo, SVD
Hiruk pikuk kata bersuara
Semuanya nampak semangat ‘bicara.’ Suara-suara dalam kata ditembakkan. Entah apa sebenarnya sasaran di balik itu? Sepertinya ada perang kata-kata bersuara. Siapa mau dengarkan siapa? Itulah yang sering terjadi.
Terkadang pula ruang percakapan tak ubah bagai satu arena kompetisi pencitraan. Ini bukan pada soal ketrampilan atau tentang seni bicara entah siapakah yang terindah penuh pikat dan terutama berisi dalam orasi. Bukan itu. Yang tejadi bahwa masing-masing ingin tunjukan bahwa dialah yang punya pengetahuan ‘lebih dan luas.’
Ada lagi yang tak mau ‘mengalah.’ Dan lalu litaniakan sejumlah pengalaman yang harus diketahui oleh siapapun pendengar. Maka, di sini, bicara yang dimeterai ad intentionem pencitraan diri memang tak terhindar. Sebab di situ orang butuh pengakuan akan pengetahuan dan pengalaman.
Inflasi kata dan bicara vs ‘ruang kosong’
Terkadang ungkapkan kata dalam bicara nampak teramat semangat. Namun itu tak berawal dari sebuah sikap ‘mendengarkan yang utuh dan lengkap.’ Sering terjadi, “Konselor terlalu bersegera memecahkan masalah.” Itu pun yang terjadi dengan siapapun yang getol sekali memberi nasihat. Entah duduk persoalan seperti apa persisnya sebenarnya ia sendiri belumlah paham.
Tidak kah ‘kaum yang bikin diri sendiri terkesan saleh’ tergoda berat untuk tumpahkan segala pengalaman ‘awan gemawannya’? Jika mesti realistis, sebenarnya yang terjadi adalah ketidakpedulian pada yang mendengarkan. Sharing rohani yang semestinya dialogal berubah total dalam alur monologal. Sebab ‘kaum saleh’ itu sudah merasa diri sebagai ‘kaum sakral,’ pun bahkan telah jadi ‘agen surga’ di dunia fana ini. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sebagai akibat?
Sebuah ‘ruang kosong’ belumlah tercipta. Iya, sama sekali tak dibangun alam ‘ramah ungkapan kata hati, apa adanya dan sejujur-tulusnya. Padahal, kata sibijak, mesti dikreasi sebuah ‘ruang kosong.’ “Menciptakan tempat seperti itu berarti memberi waktu, dukungan dan dorongan, membiarkan orang lain bertanya… membiarkan mereka mengenali pertanyaan mereka.”
Kita butuh spasi mendengarkan
Dan lagi, di alam ‘ruang kosong’ itu, tak sekedar ada ungkapan kata-kata datar yang terdengar lembut, tetapi tumpahan rasa kesal dan bahkan amarah gemuruh mesti terdengar jelas. Di situlah, disinyalir, tak bolehlah segera ada arahan, nasihat saleh, petunjuk pasti yang siap pakai sebagai jawaban atas semuanya. Tidak kah sesama mesti ‘jujur dan seadanya’ di dalam kata dan rasa hatinya?
Katanya, seturut salah satu dari indikasi kecerdasan spiritual (SQ), satu yang terbaik adalah “Lebih banyaklah bertanya apa sebab (mengapa) ketimbang menyatakan dan memastikan tentang orang lain atau tentang sesuatu.”
Belum apa-apa, namun sudah pastikan!
Mari ambil satu pengandaian sekadarnya: Melihat anak tetangga sedikit bermuram wajah tak berseri, mayoritas dalam kelompok telah pastikan apa yang telah terjadi! Tanpa kejelasan dari mana kepastian itu berawal dan dibangun. Selalu ada tendensi bikin rumor, gejolak nan heboh tanpa telaah sebab musababnya. Tetapi?
Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mayoritas kelompok itu telah ciptakan jaraknya sendiri dari si anak tetangga itu. Dan semuanya lalu sekian keasyikan untuk saling menyesatkan dengan fantasi dan pengandaian liarnya sendiri. Tidak kah di sini sebenarnya ‘suatu ruang kosong telah diabaikan dan tak diciptakan?’ Lalu kita pastikan ‘seenaknya’ mengenai anak tetangga itu.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel