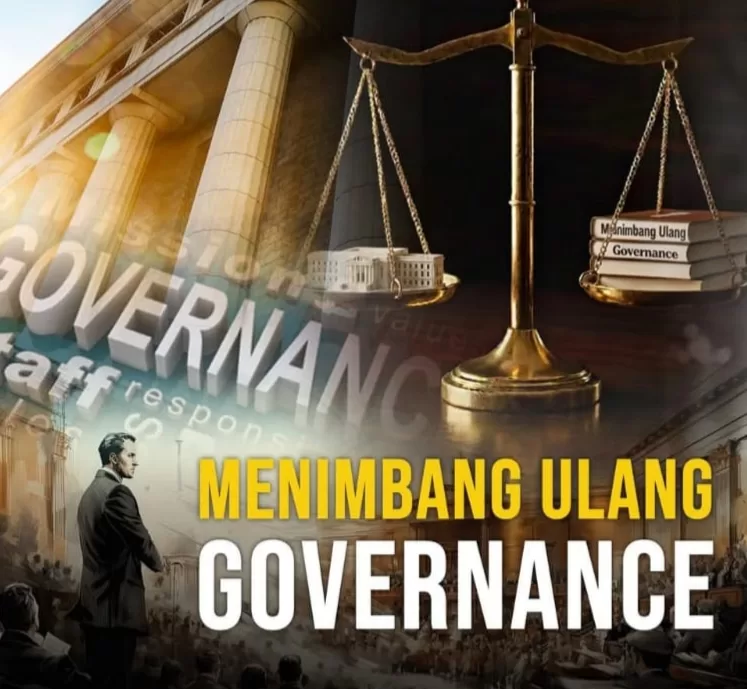DIY, infopertama.com – Dalam rangka Dies ke-60 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Prodi Ilmu Pemerintahan meluncurkan buku: “Menimbang Ulang Governance”.
Dr. Gregorius Sahdan, M.A, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, menyebut bahwa buku ini merupakan hasil karya, prakarsa dan inisiatif bersama dosen-dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan mereka dalam membangun bangsa melalui karya-karya Tri Dharma yang lebih otentik dan bermakna.
Menurutnya, dalam dua dekade terakhir, istilah governance menjadi mantra utama dalam wacana pembangunan, kebijakan publik, dan reformasi pemerintahan. Pemerintah, lembaga donor internasional, dan akademisi berlomba-lomba mengadopsi paradigma governance sebagai resep untuk mengatasi kemiskinan, korupsi, dan stagnasi pembangunan.
Namun, di balik kepopulerannya, konsep governance, di dalamnya mengandung problem epistemologis dan politis yang cukup serius. Salah satu pemikir yang menawarkan kritik tajam terhadap logika governance adalah James Ferguson, seorang antropolog politik yang dikenal melalui karya-karyanya tentang pembangunan (development) dan pemerintahan (governmentality) di Afrika bagian selatan.
Melalui karya klasiknya The Anti-Politics Machine (1990) dan tulisan lanjutannya seperti Global Shadows (2006) serta Give a Man a Fish (2015), Ferguson mengajak kita menimbang ulang bagaimana wacana dan praktik governance beroperasi bukan hanya sebagai kebijakan teknokratis, tetapi sebagai mekanisme kekuasaan yang membentuk cara kita memandang negara, masyarakat, dan pembangunan. Artikel Buku: Menimbang Ulang Governance, berupaya menelusuri governance dalam konteks kontemporer, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Di Indonesia kata Gregorius Sahdan, Konsep governance muncul sebagai respons terhadap krisis negara pasca-Perang Dingin, ketika banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dinilai gagal memenuhi fungsi-fungsi dasar pemerintahan. Lembaga seperti Bank Dunia kemudian mempopulerkan istilah governance untuk menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, governance tidak hanya menyangkut pemerintah (government), melainkan juga keterlibatan aktor non-negara seperti sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik.
Namun, pendekatan governance sering kali mengaburkan persoalan kekuasaan dan politik. Ia mengasumsikan bahwa governance adalah soal manajemen yang rasional dan netral, bukan arena konflik kepentingan. Di sinilah para penulis menawarkan cara pandang yang berbeda: governance bukan sekadar “cara memerintah”, melainkan praktik diskursif yang memproduksi kebenaran, otoritas, dan ketertiban sosial tertentu.
Sebagaimana Gregorius Sahdan menguip buku: The Anti-Politics Machine dari Jams Ferguson yang meneliti proyek pembangunan di Lesotho. Ia berargumen bahwa proyek pembangunan internasional tidak hanya gagal karena salah diagnosis, tetapi karena ia secara sistematis menghilangkan politik dari persoalan sosial.
Dengan kata lain, pembangunan menjadi “mesin anti-politik” (anti-politics machine)—sebuah mekanisme yang mengubah masalah ketimpangan dan kekuasaan menjadi persoalan teknis dan administratif.
Logika yang sama, menurut Ferguson, juga berlaku dalam wacana governance. Ketika lembaga internasional berbicara tentang governance, yang mereka lakukan bukan hanya memberikan solusi teknis, melainkan membingkai ulang relasi kekuasaan. Korupsi, kemiskinan, atau kegagalan negara tidak lagi dipandang sebagai akibat struktur politik atau ketimpangan global, melainkan sebagai hasil “kurang baiknya tata kelola.” Dengan cara ini, governance menjadi alat depolitisasi: masalah politik diubah menjadi masalah manajerial.
Dalam kerangka ini, governance adalah bagian dari logika governmentality neoliberal, yaitu cara mengatur populasi bukan lagi melalui negara yang dominan, tetapi melalui mekanisme pasar, jaringan, dan tanggung jawab individu.
Dalam buku: Global Shadows, Ferguson memperlihatkan bagaimana logika governance neoliberal membentuk struktur sosial baru di Afrika. Negara diposisikan bukan sebagai aktor utama pembangunan, melainkan sebagai fasilitator bagi investasi dan bantuan luar negeri. Akibatnya, kewenangan publik bergeser ke tangan lembaga internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Ini menandai pergeseran besar dari pemerintahan oleh negara menjadi pemerintahan melalui jaringan.
Jika ditarik ke konteks Indonesia, kita dapat melihat gejala serupa. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat sering kali dibungkus dalam wacana good governance, tetapi di balik itu terselip logika rasionalisasi dan efisiensi yang meniru model korporasi. Lembaga donor dan konsultan internasional mendikte bagaimana “tata kelola yang baik” harus dijalankan, sering kali tanpa memperhitungkan keragaman sosial, politik, dan budaya lokal.
Buku: Menimbang Ulang Governance mengembangkan gagasan baru tentang pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ini berbeda dengan pandangan neoliberal yang menekankan produktivitas dan kemandirian, tetapi juga bagaimana rakyat mengambil peran di dalamnya.
Dari sini, kita belajar bahwa governance tidak harus selalu dimaknai dalam bingkai efisiensi dan kontrol, tetapi sebagai bentuk pengelolaan kehidupan bersama (the management of life) yang berlandaskan keadilan distributif dan pengakuan terhadap martabat manusia.
Dengan demikian, governance dapat dipulihkan dari jebakan teknokratis menuju arena politik yang lebih etis dan reflektif. Gregorius Sahdan mengatakan bahwa: “Menimbang Ulang Governance ” dapat dijadikan sebagai rujukan kita dalam membaca Indonesia. Indonesia pasca-reformasi sering dipuji sebagai contoh sukses penerapan prinsip good governance melalui desentralisasi, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan governance justru mereproduksi ketimpangan baru. Desentralisasi melahirkan oligarki lokal; partisipasi masyarakat sering hanya bersifat simbolik; dan transparansi diukur melalui indikator administratif, bukan perubahan substantif.
Dalam perspektif ini, governance di Indonesia berfungsi lebih sebagai “mesin representasi” ketimbang ruang politik sejati. Ia menciptakan citra seolah-olah rakyat berpartisipasi dan negara berjalan baik, padahal struktur kekuasaan tetap tidak berubah. Program-program pembangunan yang didorong oleh lembaga donor pun sering memindahkan tanggung jawab dari negara ke masyarakat tanpa menyediakan sumber daya yang memadai.
Menimbang ulang governance berarti mengembalikan politik ke dalam tata kelola: mengakui bahwa setiap kebijakan publik adalah hasil negosiasi kepentingan, bukan sekadar desain teknis. Buku ini mencoba membaca setiap inisiatif governance dengan pertanyaan kritis: Siapa yang diuntungkan? Siapa yang disingkirkan? Kekuasaan siapa yang diperkuat?
Buku ini, membantu kita menyingkap lapisan tersembunyi dari wacana governance. Ia menunjukkan bahwa di balik jargon efisiensi dan akuntabilitas, terdapat logika depolitisasi dan reproduksi kekuasaan global. Governance bukanlah konsep netral; ia adalah perangkat politik yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang dianggap kompeten, dan siapa yang disenyapkan.
Dengan memahami bagaimana governance bekerja sebagai anti-politics machine, kita dapat merancang bentuk governance yang lebih emansipatoris—yang mengakui konflik, menghormati konteks lokal, dan menempatkan keadilan sosial di pusatnya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menimbang ulang governance berarti menolak menjadi sekadar objek dari tata kelola global, dan mulai membangun tata kelola yang berpihak pada rakyat.
Dengan demikian, mengajak kita semua, tidak sekadar memperbaiki governance, tetapi mempolitisasi ulang konsep itu: menjadikannya arena perjuangan untuk menentukan bagaimana kita ingin hidup bersama, siapa yang mengatur, dan atas dasar nilai apa kekuasaan dijalankan. Jika anda tertarik, silahkan ikuti peluncuran buku ini tanggal 13 November 2025.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel