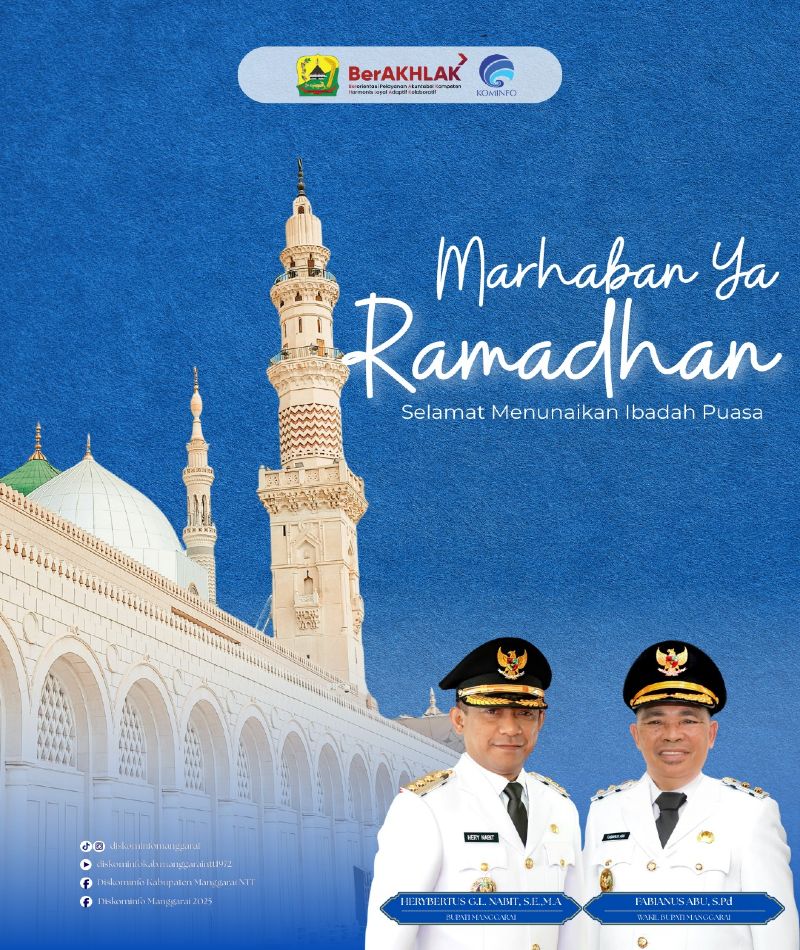Oleh Jefrin Haryanto★
infopertama.com – Boleh jadi akan ada seorang ayah atau banyak ayah yang protes dengan tulisan saya kali ini. Tulisan ini bahkan saya tulis saat saya berada di luar rumah. Situasi dimana sebenarnya saya sedang berjauhan dengan anak-anak saya. Anak-anak yang tumbuh besar dengan sedikit sekali sentuhan seorang ayah. Sesekali saya bisa punya argument bahwa saya adalah laki-laki yang harus selalu ada di luar rumah dan mencari nafkah. Lalu ketika kau pulang ke rumah, saat anak-anakmu sudah terlelap dalam tidurnya.
Saya adalah satu dari banyak ayah di negeri ini yang hampir tak punya waktu untuk anak-anak saya. Membayangkan bagaimana anak-anak tumbuh besar tanpa kehadiran yang mendalam dari seorang ayah. Mengerikan jika menyimak studi Department of Health & Human Services Amerika melihat efek kurangnya peran ayah. Anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya lebih rentan terhadap penyakit fisik dan mental, kejahatan pornografi, dan prostitusi. Anak laki-lakinya cenderung terlibat dalam perkara kriminal, sementara anak perempuannya rawan mengalami kehamilan remaja. Mereka juga lebih mudah terlibat dalam masalah alkohol dan putus sekolah. Mereka pun merokok 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan anak-anak yang dekat dengan ayahnya. Laki-laki pelaku KDRT umumnya memiliki ayah yang juga pelaku KDRT, dan anak-anak perempuan mereka cenderung mendapat pasangan pelaku KDRT.
Faktanya Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia sebagai negeri tanpa ayah atau fatherless country. Artinya, anak-anak Indonesia tumbuh dengan sangat sedikit sentuhan ayah. Satu tingkat di atas Indonesia, ada Amerika Serikat sebagai runner up. Di sana, 1 dari 4 anak hidup tanpa ayah. Ini terjadi kebanyakan karena tingginya tingkat perceraian dan hubungan tanpa pernikahan.
Pola patrilineal yang cukup kental di Indonesia cukup mendukung perkembangan Indonesia menjadi fatherless country. Posisi ayah yang harus selalu diutamakan karena dinilai sudah berjuang keras dan lelah mencari nafkah sehingga sudah tidak perlu dibebani lagi dengan tangisan anak, atau bermain bersama anak. Bahkan tidak jarang, dulu sewaktu kecil kita mendengar ucapan ibu atau nenek kita untuk tidak mengganggu istirahat ayah atau kakek kita. Padahal terkadang ayah hanya memiliki waktu sebentar di rumah dibandingkan seorang ibu untuk mempunyai pengalaman berkualitas bersama anak.
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel